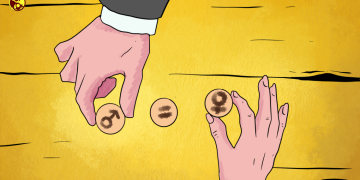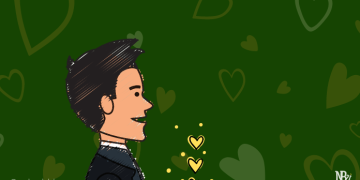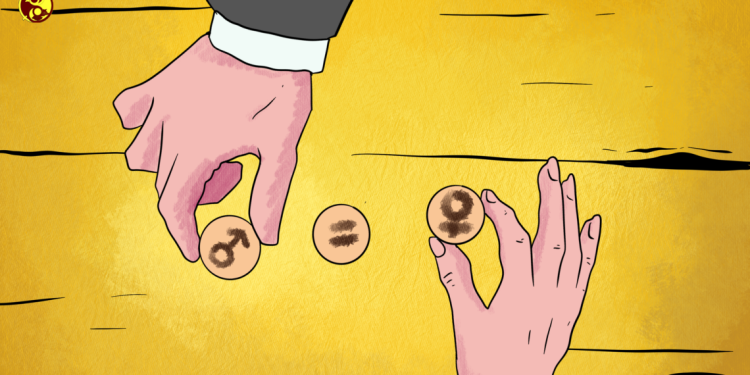Judul Buku: Manual Mubadalah
Penulis: Dr. Faqihuddin Abdul Kodir
Penerbit: USM
Tahun Terbit: 1 Mei 2019
Tebal: 156 hlm
Mubadalah.id – Sejak kuliah di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), aku jadi semakin tertarik belajar tentang kesetaraan gender. Dalam beberapa pertemuan, aku sering mendengar bahwa budaya patriarki ternyata tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki.
Dari situ, aku mulai mempertanyakan banyak hal. Salah satunya, mengapa perempuan masih terus mengalami ketidakadilan, padahal Islam sendiri dengan tegas melarang kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.
Rasa penasaran itu akhirnya membawaku pada buku Manual Mubadalah karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir. Dari buku ini, aku mulai belajar tentang relasi yang saling dan setara. Aku semakin memahami bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh kasih sayang, termasuk dalam memandang perempuan. Islam tidak pernah membenarkan kekerasan terhadap perempuan
Hal ini dapat dilihat dari catatan sejarah Islam yang membebaskan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan. Pada masa jahiliyah, perempuan benar-benar tidak dianggap sebagai manusia.
Kelahiran anak perempuan dipandang sebagai aib dan malapetaka, sehingga ada keluarga yang memilih menguburnya hidup-hidup. Perempuan juga diperlakukan seperti barang: bisa dihadiahkan, diperjualbelikan, diwariskan, bahkan dibuang begitu saja
Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itu, Islam datang dan mengangkat derajat perempuan. Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia yang utuh dan bermartabat, bukan benda yang bisa diperlakukan semaunya. Nabi Muhammad saw. pun berulang kali berpesan kepada para pengikutnya agar memperlakukan perempuan dengan baik.
Nilai Keadilan
Dari sini aku semakin paham bahwa Islam sejak awal sudah mengajarkan nilai keadilan dan kebaikan bagi perempuan. Lalu pertanyaannya, mengapa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi? Bahkan sering kali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai “pengikut Nabi”.
Dalam Manual Mubadalah, Dr. Faqihuddin menjelaskan bahwa persoalan utama yang perlu kita benahi agar perempuan tidak lagi mengalami kekerasan.
Pasalnya, selama ini, relasi antara laki-laki dan perempuan kerapkali dibangun secara timpang. Perempuan diposisikan sebagai manusia kelas dua. Sehingga dianggap wajar untuk dikontrol, diperlakukan buruk, atau bahkan mengalami kekerasan.
Karena itu, relasi yang timpang ini perlu kita ubah menjadi relasi yang mubadalah, yaitu relasi yang berkesalingan.
Kata mubadalah berasal dari bahasa Arab badala, yang berarti mengganti, menukar, atau mengubah. Dari sini lahir konsep mubadalah sebagai cara pandang dalam hubungan antarmanusia yang menekankan kemitraan, kesalingan, dan timbal balik. Prinsip ini bukan sekadar soal memberi atau menerima, tetapi tentang bagaimana relasi kita bangun agar saling menguatkan.
Dalam perspektif mubadalah, relasi antarmanusia seharusnya saling memberi manfaat, saling memuliakan, dan saling menumbuhkan. Prinsip kesalingan ini bisa kita terapkan dalam hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam rumah tangga
Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri seharusnya bekerja sama, baik dalam pekerjaan domestik, pekerjaan publik, maupun dalam menjaga keutuhan relasi agar tercapai keluarga yang sakinah. Kerja sama ini penting agar tidak ada satu pihak yang menanggung beban lebih berat sendirian.
Kerja Domestik
Di lingkunganku, aku sering melihat istri yang kelelahan karena harus mengerjakan hampir seluruh pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, merawat anak, hingga mengurus berbagai keperluan keluarga, termasuk suami. Bahkan ada perempuan yang juga bekerja mencari nafkah, tetapi tetap terbebani dengan pekerjaan domestik seorang diri.
Sementara suaminya enggan mengambil peran, baik dalam urusan rumah tangga maupun ekonomi.
Dalam studi gender, kondisi ini kita kenal sebagai beban ganda, dan ia merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.
Melihat realitas sosial seperti ini, aku merasa perspektif mubadalah menjadi sangat penting bagi setiap pasangan. Relasi yang berkesalingan mencegah lahirnya dominasi satu pihak atas pihak lain.
Keduanya dituntut untuk saling berbagi peran. Tentu saja, sebagaimana disampaikan Dr. Faqihuddin, pembagian peran itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Artinya, pembagian peran tidak bersifat kaku. Setiap pasangan bisa mendiskusikan bersama siapa melakukan apa. Semua dijalani secara sadar, tanpa paksaan, apalagi ancaman. Inilah relasi yang diharapkan Islam: pernikahan yang sehat, di mana kedua pihak sama-sama bertanggung jawab, bukan relasi yang membiarkan satu pihak terus kelelahan.
Realitas seperti inilah yang membuat aku sadar bahwa keadilan dalam relasi tidak cukup hanya dibicarakan sebagai nilai ideal. Ia perlu cara pandang yang jelas dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Di titik inilah perspektif mubadalah menjadi relevan, karena ia menawarkan kerangka relasi yang adil dan setara.
Bagi aku, Manual Mubadalah bukan sekadar buku tentang tafsir atau konsep gender. Buku ini menjadi alat untuk menguji ulang relasi timpang yang selama ini mereka anggap wajar. Sebab relasi tidak boleh kita bangun di atas kuasa, melainkan atas dasar kesalingan dan tanggung jawab bersama. []